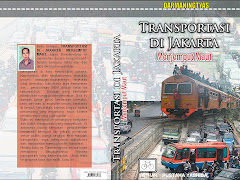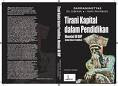Filsuf satu ini kasihan juga nasibnya. Memang benar ungkapan, kalau tak kuat berfilsafat jadinya ya gila atau bunuh diri. Filsuf yang juga hobi bikin puisi ini pada zamannya tergolong aneh. Dia mengatakan, tanaman seperti halnya hewan dan manusia juga punya hasrat seks. Mungkin maksudnya sama-sama berkembang biak. Namun oleh masyarakat awan pendapat begitu dijadikan bahan tertawaan. Empedokles pun dicemooh setengah gila.
Ajaran filsafat Empedokles sesungguhnya sangat alamiah. Hanya saja pada waktu hidupnya, mayoritas manusia lebih mempercayai mitos-mitos, otoritas dewa dan mistis, maka cara berfikir model Empedokles dianggap nyeleneh. Filsuf kelahiran Akragas, Sisilia ini mengombinasikan sikap hidup mistis yang sudah mentradisi di masyarakatnya dengan berfikir filsafat alamiah sebagai hal baru.
Empedokles menyetujui keyakinan, bahwa di alam semesta ini tiada ruang kosong. Alam semesta tersusun dari empat anasir utama, yaitu air, udara, api dan tanah. Keempat anasir ini mempunyai kualitas yang sama, yaitu tidak berubah. Segala sesuatu di alam semesta pasti terdiri dari empat anasir. Perbedaan benda-benda antara satu dengan lainnya akibat campuran yang berbeda-beda. Misalnya tulang terdiri dari dua bagian anasir tanah, dua bagian anasir air dan empat bagian anasir api. Demikian seterusnya.
Filsuf yang tidak begitu terkenal dan jarang dikutip pendapatnya dalam sejarah filsafat, juga mengembangkan teori evolusi tentang penciptaan alam semesta. Pada mulanya ada dua kekuatan saling berlawanan, yaitu cinta (filotes) dan benci (neikos). Cinta memiliki sifat menyatukan, sedangkan benci bersifat memisahkan. Dua kekuatan itu sekian lamanya mempersatukan empat unsur alam semesta secara harmonis. Namun kekuatan benci secara berangsur-angsur merobek keselarasan yang ada.
Melalui empat zaman, cinta dan benci silih berganti saling mendominasi. Pada zaman pertama, cinta lebih dominan. Alam semesta bagaikan bola yang keempat anasirnya menyatu secara sempurna.
Pada zaman kedua, kekuatan benci mulai mengimbangi kekuatan cinta. Makhluk-makhluk hidup dapat mati. Empedokles menyatakan hidup di zaman kedua ini.
Pada zaman ketiga, kekuatan benci akhirnya mendominasi. Kekuatan cinta tersingkir di paling pinggir. Alam semesta menjadi kocar-kacir. Mungkin dalam bahasa sekarang sejenis dengan kiamat.
Pada zaman keempat, terjadi lagi keseimbangan. Kekuatan cinta memperbaiki kerusakan-kerusakan sehingga menuju ke harmonisasi.
Uniknya menurut Empedokles, tahap-tahap tersebut berulang silih berganti secara teratur. Dalam menjelaskan berbagai pertanyaan mengenai alam semesta, asal-usul dan pekermbangannya, secara umum dimaklumi oleh masyarakat kala itu.
Hal paling kontoversial adalah ketika Empedokles menjelaskan tentang penyucian jiwa. Empedokles pun mempercayai adanya perpindahan jiwa atau yang dikenal sebagai inkarnasi. Dia mengajarkan ilmu menyucikan diri. Empedokles pun menyatakan sudah sampai pada tahap setara dengan Sang Maha Suci. Tentu saja itu mengundang reaksi masyarakatnya.
Orang-orang yang tidak dapat menyetujui puncak filsafatnya meminta bukti tingkat kesucian Empedokles. Pada usia ke-60 tahunnya sang filsuf mengajak masyarakat untuk mendaki Gunung Etna atau menunggu di kaki bukit bagi yang tidak mau mendaki. Hanya beberapa orang saja bersedia mengikuti Empedokles. Itu pun tidak sampai ke puncaknya.
Sedangkan Empedokles menengadah ke langit sejenak, begitu sampai di puncak Gunung Etna. Dia berdiri tegar di bibir kawah mengaga ditingkahi asap bau belerang. Nampaknya Empedokles sudah mentok berfilsafat. Serta merta sang filsuf meloncat ke kawah Gunung Etna. Empedokles terpanggang hidup-hidup, menjadi bubur panas dalam adukan panasnya lahar kawah Etna. (***)